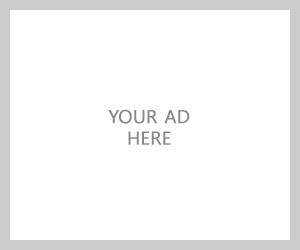Dibawah pohon duku kembar bocah itu lahir. Membawa nasibnya sendiri, mencoba menyapu dunia. Dikelilingi duku kembar yang entah kapan jumeneng dalam kehidupan.
Dibawah pohon duku kembar bocah itu lahir. Membawa nasibnya sendiri, mencoba menyapu dunia. Dikelilingi duku kembar yang entah kapan jumeneng dalam kehidupan.Dalam kesederhanaan, bocah itu bermain dibawah duku kembar. Melingkar-lingkarkan tangannya memeluk batang duku kembar, tapi tidak pernah sampai. Duku kembar itu ibarat ibunya yang selalu memeluk dengan hangat setiap pagi.
Tanah dibawah duku kembar sangat halus, lebih halus dari keramik dasar lautan. Daun-daun duku kembar berhamburan menutupi lantai tanah, tempat bocah dengan sapu ditangan bermain. Bocah itu membawa sapu hendak meratakan tanah dibawah duku kembar. Gemuruh semangat menerbangkan daun-daun duku kembar.
Dibawah duku kembar suasana sangat teduh. Kadang-kadang terdengar tawa, kadang terdengar tangis. Bocah-bocah terlihat berlari-larian. Banyak sekali permainan dibawah duku kembar. Bocah itu membuat kotak persegi berurutan. lalu mencari potongan genteng untuk gaco. Dilemparkannya gaco itu ke tengah kotak persegi. Bergantian, lama sekali.
Sementara itu di pedangan, ibu bocah itu memanak nasi dengan ketela. Setelah lelah bermain bocah itu makan dengan lahapnya. Tidak ada lauk, yang ada hanya bakaran terasi dan garam yang ditaburkan ke atas nasi.
Habis duhur, bala bocah itu sudah menanti. Sambil membawa kayu panjang, bocah itu berlarian ke tengah alas. Matanya awas mengamati ketinggian. Mencari nining-nining gendong terbang. kuning, merah, hijau, satu persatu dikumpulkannya nining-nining itu. Mukanya penuh dengan ramat binatang itu. Tertawa-tawa sambil berlari pulang.
Sambil melepas letih, bocah itu duduk di bawah duku kembar. Akar duku kembar yang menjulur tak beraturan memijit tubuhnya, menghilangkan penat setelah bermain. Kemudian mereka akan nyamplongi duku kembar itu. Bagaikan mengerti keinginan anaknya, duku kembar itu akan merontokkan buahnya. Hujan duku berjatuhan semarak menghujani bocah itu. Rebutan seru terjadi, jumpalitan saling tindih. Lalu dimakannya duku itu tanpa sisa, semua tertawa.
Cakrawala disebelah barat sana semakin berwarna merah. Matahari sudah ngumpet di balik bukit Semedo. Di rumah depan mushola itu sang bocah duduk ditemani lampu senthir kakeknya. Mendengarkan kakeknya bercerita, tentang jaman perang, tentang hidup. Biasanya bocah itu mendengarkan sambil sesekali menyela, bertanya. Di rumah itu hanya ada bangku panjang dan meja panjang.
Setelah malam larut, minyak di senthir itu mulai habis. Biasanya bocah itu digendong bapaknya ke gubuk kecilnya di bawah duku kembar. Ditidurkannya di amben oleh bapaknya. Setelah itu bapaknya akan pergi ke kali, nawu air kali mencari lele. Akan dijual buat makan anak-anaknya besok hari. Sebelum subuh bapaknya sudah kembali. Ember yang dibawanya berisi banyak lele.
Malam semakin hening, burung-burung malam bersuara parau. Kelelawar sudah kenyang menikmati makannya malam ini. Hidup masih harus berjalan bagi bocah itu. bocah dengan sapu ditangan, entah sampai kapan menyapu dan akan tersapu oleh kehidupan. Dibawah pohon itu, pohon duku kembar. Lambang kerasnya kehidupan, tetapi memberi kehangatan bagi mahluk di bawahnya.
Bocah dengan sapu ditangan.